— Sebuah Gugatan dari Cinta
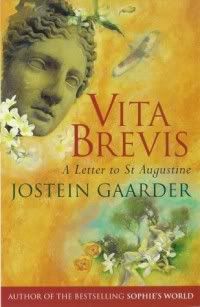 Vita Brevis amazon.com |
Beberapa waktu yang lalu, saya terlibat (tepatnya: melibatkan diri) dalam diskusi yang menyoal buku Vita Brevis — Sebuah Gugatan dari Cinta (edisi Inggrisnya berjudul That Same Flower). Mestinya buku itu cuma buku biasa yang tidak perlu dihebohkan, karena hanya berisi sebuah surat (atau beberapa buah surat yang sinambung) dari seorang perempuan tidak terkenal kepada mantan kekasih kumpul-kebonya yang telah membuahkan seorang anak lelaki.
Secara ringkas, surat pribadi itu berisi protes (itu sebabnya subjudul buku tersebut sangat pas disebut gugatan dari cinta) terhadap alasan kekasihnya meninggalkannya sebagaimana dilansir oleh kekasihnya itu dalam sebuah buku berbentuk otobiografi reflektif. Mestinya juga surat itu tidak istimewa. Ada banyak kasus serupa yang terjadi di dunia ini. Perempuan itu bukan satu-satunya perempuan di dunia yang pernah ditinggalkan dan merasa dikhianati serta disia-siakan oleh lelaki yang sangat dicintainya dan mengaku pernah sangat mencintainya pula.
Keistimewaan timbul ketika si penulis surat yang mengaku bernama Aemilia Floria itu menujukan surat-suratnya kepada Aurelius Agustinus yang kemudian lebih dikenal sebagai Uskup Hippo, yang tidak lain adalah seorang teolog besar gereja dan seorang santo. Dan yang lebih dahsyat lagi, selain memaparkan kenangan dan sikapnya atas hubungan cinta mereka di masa lalu, surat itu juga berisi kritik terhadap beberapa hal yang tertera dalam karya besar Agustinus yang berjudul Confessiones.
Terlepas dari keabsahan surat yang disebut sebagai Codex Floriae oleh Jostein Gaarder yang menerjemahkannya dari bahasa Latin ke bahasa Swedia tersebut, timbul satu kesangsian besar: Mungkinkah di jaman Agustinus (354 – 430 ZB) ada perempuan yang memiliki tingkat intelektualitas sedemikian tinggi sehingga mampu menyampaikan kritik yang sepadan dengan pemikiran-pemikiran orang sekaliber Santo Agustinus? Apalagi pada masa itu paradigma patriarkal masih sedemikian kuat mencengkeram berbagai gatra kehidupan, termasuk gereja, sehingga peran perempuan nyaris tidak termunculkan sama sekali.
Saya tidak bisa menjawab kesangsian tersebut secara tegas karena saya bukan pakar sejarah atau bahasa atau skriptologi ataupun sosio-antropologi yang berkompeten memberikan pernyataan akhir. Namun, di sisi lain, saya pun tidak bisa untuk tidak memberikan the benefit of doubts bahwa kelangkaan atau ketidaklaziman bukanlah istilah lain bagi ketidakmungkinan. Karena, menurut saya, intelektualitas kaum perempuan bukanlah produk masa kini yang baru muncul kemudian, melainkan sudah ada sejak kisah penciptaan Taman Eden.
Malah sempat terlintas pikiran nakal dalam benak saya, jangan-jangan ada bagian yang tidak tertera dalam kitab Kejadian dimana Adam sudah lebih dulu kalah berdebat melawan ular dan kemudian mengajukan Hawa sebagai palang-pintu terakhir pembela manusia. Atau, Adam malah tidak sempat melakukan perdebatan itu karena sudah terlalu letih memberi nama semua binatang ciptaan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu.
Sore tadi, kebetulan saya membuka-buka kembali buku lama Mencari Bulir-bulir Gandum yang merupakan kumpulan tulisan padat-ringkas-bernas karya [almarhum] Romo Dick Hartoko, SJ. Dalam artikel nomor 4 yang diberinya judul Surat-menyurat sebagai Sarana Pewartaan, Romo Dick menuliskan:
Agustinus menguraikan pandangannya mengenai rahmat dan dosa lewat surat-surat kepada teman-teman di Roma. Dan ingat, banyak di antara mereka adalah wanita. Lalu Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Jesuit, lewat surat-suratnya kepada wanita-wanita, menguraikan ide-idenya tentang hidup rohani. Demikian juga Fransiskus dari Sales. (hal. 5)
Saya rasa, saya bisa mempercayai tulisan Romo Dick karena beliau adalah seorang yang sangat akrab dengan dunia literatur dan pernah mendalami bidang sejarah di Tilburg (1949 – 1952 ZB). Sehingga saya yakin beliau tidak asal menulis, apalagi yang berkenaan dengan tokoh-tokoh sebesar Agustinus dan Ignatius.
Dengan demikian, nyatalah bahwa para tokoh besar gereja —termasuk Agustinus yang menjadi topik dalam diskusi tersebut— kerap berkorespondensi dengan para perempuan dalam soal-soal yang tidak sederhana. Atau, dengan kata lain, di masa-masa lampau —bahkan di jaman Agustinus pada abad keempat—, tidak sedikit perempuan yang sanggup terlibat dalam soal-soal filsafat dan teologi yang kala itu —bahkan hingga kini pun!— kerap dianggap sebagai kawasan khusus yang didominasi oleh kaum lelaki.
Namun kesangsian besar di atas belum sepenuhnya terjawab tuntas. Malah menimbulkan pertanyaan baru: Apakah para tokoh pemikir gereja itu berkirim surat secara searah ataukah terjadi komunikasi timbal-balik di mana terjadi pertukaran wacana antara mereka? Dan mengapa kepada para perempuan?
Masih dalam bingkai the benefit of doubts, saya rasa para tokoh gereja itu bukannya sekedar iseng tatkala berkirim surat dan berdialog dengan para perempuan (yang kebanyakan dari mereka tetap tidak dikenal luas). Amatlah naif jika saya berpikir bahwa mereka melakukannya demi memuaskan libido berkotbah (monolog) yang hanya ditelan bulat-bulat dan tidak mungkin ditanggapi secara serius dan seimbang oleh para perempuan itu.
Sebaliknya, sangat boleh jadi mereka —entah sadar entah tidak— menempatkan para perempuan dalam posisi sebagai penolong yang sepadan sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 2:18, yang menyiratkan kemampuan perempuan untuk mengimbangi dan melengkapi keberadaan kaum lelaki, halmana intelektualitas tidak bisa dikecualikan. Apalagi dalam soal kepedulian dan kepekaan akan sifat-sifat dan perasaan yang sangat manusiawi, yang malah kerap luput dari perhatian kaum lelaki (yang kemudian digeneralisasi bahwa kaum lelaki lebih mengutamakan rasio sedangkan kaum perempuan lebih mengutamakan perasaan).
Dari bersilancar di internet, saya temukan banyak analisis yang sangat menarik mengenai makna kata Ibrani ezer k'negdo yang diterjemahkan sebagai penolong yang sepadan. Padahal, makna dari masing-masing kata tersebut tidaklah sesederhana itu.
Dalam bahasa aslinya, ezer yang diterjemahkan sebagai penolong (helper) tidak mengimplikasikan posisi inferior atau subordinasi (assistant, servant, second-rate attendant), melainkan setara atau malah lebih tinggi. Bahkan, dalam Alkitab Yahudi, kata itu hampir selalu secara eksklusif dikenakan untuk Allah (bdk. Keluaran 18:4, Mazmur 33:20, 70:6, 115:9, 121:1-2, 146:5, Hosea 13:9). Sedangkan k'negdo berasal dari kata neged yang berarti melawan, bertentangan (against, opposite).
Tentu saja penggandengan kedua kata tersebut menghasilkan makna yang ganjil, sehingga melahirkan banyak penafsiran, mulai dari yang moderat hingga yang sangat ekstrim (misalnya penafsiran bahwa perempuan adalah penolong yang berasal dari dan atas nama Allah sehingga lebih superior dibanding lelaki).
Namun demikian, ada benang merah yang pada intinya menegaskan bahwa perempuan adalah mitra setara lelaki yang bersifat melengkapi, menyempurnakan, menyelamatkan (to rescue, to save), atau menguatkan (to be strong) dalam harmoni. Sehingga akhirnya dapat mengerti mengapa Adam menyebut Hawa sebagai tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, yang mengandung pengakuan atas ketidaksempurnaannya dalam kesendirian.
Lalu saya ingat pula perjalanan hidup Juan de Yepes (1540 – 1591 ZB) yang sangat boleh jadi tidak akan menampakkan kecemerlangan pemikiran spiritualnya kalau saja Teresa dari Avila tidak membujuk, membimbing, dan mendorongnya untuk menempa proses kreatif dan imajinatifnya melalui media musik, puisi, dan dongeng. Tanpa Teresa, barangkali Juan hanya akan tinggal sebagai seorang paderi Karmelit pemalu dan rendah diri (barangkali karena tubuhnya yang pendek) yang tidak dikenal, bukannya menjadi pujangga dan mistikus besar gereja yang menyandang nama Yohanes dari Salib.
Terngiang sebuah pepatah klasik yang menyatakan, "Di balik setiap lelaki yang sukses, terdapat seorang perempuan yang kuat". Saya rasa, ke dalam kategori itu termasuk juga perempuan yang harus menanggung deritanya seorang diri, yang dengan berat hati harus mematahkan belenggu yang bisa menghalangi langkah sang lelaki menggapai bintang kejayaannya. Bukan karena mereka kalah kelas dalam hal intelektualitas dibanding lelaki, melainkan karena mereka lebih tangguh dalam menyimpan rahasia, walau dengan luka dan airmata. Sedangkan hidup ini terlalu singkat untuk mengurainya. Vita brevis.
— Beth: Selasa, 27 September 2005 03:16









