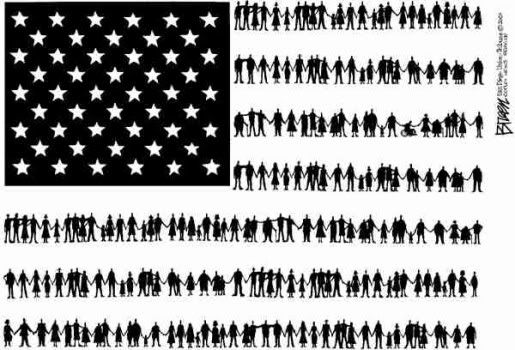Malam masih amat muda tatkala perempuan itu duduk di sofa di hadapanku berseberang
meja. Kutoleh sekejap lalu meneruskan membaca email melalui PDA. Apa peduliku? Setiap
orang berhak duduk di kursi mana pun yang disukainya.
"Boleh minta rokok sebatang?" tanyanya mengoyak keasikanku.
Kuangkat wajahku dari ketertundukan. "Silakan," sahutku sambil menyorongkan
bungkus rokok yang tergeletak di meja diapit pemantik api Zippo dan asbak keramik berisi
dua puntung padam.
Perempuan itu mencabut sebatang rokok. Alih-alih menyalakan pemantik api a-la gentleman
dalam film, aku hanya mendorong Zippo ke arahnya.
"Terimakasih," katanya sambil menghembuskan asap lewat mulut dengan tiupan
kuat.
Pasti aku sudah melupakan kehadirannya jika dia tidak bicara tepat setelah kutuntaskan
membaca dan membalas beberapa email.
"Tidak main?" tanyanya.
Aku menggeleng sambil mematikan PDA. "Tidak suka," kataku menegaskan.
"Terus, ngapain ke sini?"
Keningku berkerut. Untuk apa menanyakan alasan kehadiran seseorang di tempat yang boleh
dikunjungi siapa pun termasuk yang tidak punya alasan?
"Mengawani sepupu," tukasku datar dengan gerakan dagu menunjuk Ronny yang
beberapa bulan ini amat gandrung boling.
"O, Pak Ronny."
"Kenal?"
"Satu klub dengan temanku," sahutnya seraya menunjuk lelaki yang bermain di
jalur lain. Kukenali Ishak yang belasan tahun lebih tua dibanding Ronny yang seumuranku.
Sedangkan perempuan itu kutaksir tak kurang sepuluh tahun lebih muda dariku. Entah
bagaimana cara pertemanan dua insan berbeda jenis kelamin yang terpaut duapuluhan tahun.
Ah, bukan urusanku!
"Kamu tidak main?" tanyaku kemudian. Entah kenapa aku jadi rajin
berbasa-basi. Biasanya aku amat canggung pada perempuan, apalagi di tempat umum, sehingga
kerap diolok bahwa padananku adalah perempuan "rumahan" atau
"sekolahan". Peranku dalam berbagai kesempatan adalah menjadi manusia periferal
di tepi kerumunan sebagai figuran yang luput dari hitungan.
"Sedang malas," katanya sambil mematikan rokok di asbak.
"Biasa main di sini?"
"Seminggu sekali. Lain hari, di Kuningan atau Ancol."
"Minimal tiga kali seminggu, jago dong."
"Ah, biasa saja."
"Suka ikut turnamen?"
"Kalau hadiahnya menarik," jawabnya sambil tersenyum.
Kudorong bungkus rokok dan Zippo sekalian ke dekatnya. Rokok dia selipkan di bibir.
Tangan kanannya yang menggenggam Zippo melakukan dua gerakan tanpa jeda: ibu jari
mengungkit terbuka tutup Zippo dengan denting khas, lalu berbalik memutar roda gigi
penggesek batu api menyalakan sumbu. Setelah ujung rokok membara, tangannya menyentak ke
kiri sehingga Zippo menutup memadamkan api. Kendati hanya style dasar, belum
pernah kulihat seorang perempuan memakai Zippo dengan bergaya.
"Perokok profesional juga rupanya," komentarku.
"Belasan tahun mencumbu nikotin," dia tersenyum.
Baru kusadari matanya pun memancarkan senyum di balik bulu mata yang —juga baru
kusadari— amat lentik. Entah asli atau palsu, tampak pantas hadir di sana. Telanjur
memandang, kuteruskan menelusur kening, hidung, pipi, bibir, dan dagunya. Tanpa bedak,
hanya saputan samar gincu merah pucat di bibir. Walau tidak cantik seturut kriteriaku,
semua tertata serasi. Bekas luka kecil di tepi kelopak mata kirinya bahkan menjadi aksen
pemanis. Ya, manis adalah istilah yang cocok. Hitam manis, tepatnya. Eksotis.
"Ada yang aneh di mukaku?" tanyanya memergoki.
Aku menggeleng. Lambaian Ronny di depan meja kasir menyelamatkanku dari kekikukan.
"Ronny sudah selesai. Aku duluan," kataku sambil bangkit.
"Thanks rokoknya."
Aku mengangguk kecil sambil menjajari Ronny ke pintu keluar.
"Apa yang kalian bicarakan?" tanya Ronny setelah kami duduk di mobil.
"Siapa?"
"Kamu dan perempuan tadi, Julia."
"Tidak ada. Hanya minta rokok."
"Hati-hati."
"Kenapa?"
"Bukan perempuan rumahan dan sekolahan."
"Karena bersama Ishak si hidung belang?"
Ronny hanya berdehem.
Aku tak berminat meneruskan. Bergunjing bukanlah kegemaranku. Lagipula, siapakah Julia
sampai perlu kubicarakan? Hanya seorang perempuan yang sejenak lewat di satu malam yang
sangat biasa untuk menumpang menghirup dan mengepulkan kabut nikotin dua batang rokokku.
Ternyata, masih berkali-kali kujumpa Julia. Setelah kali kesekian, dia tak lagi sungkan
duduk di hadapan atau sampingku. Malah sepertinya sengaja mencari. Dan, laksana ritual,
aku pun langsung menyodorinya rokok berikut Zippo.
Kadang, tak satu pun kata terucap sampai aku pulang, hanya menambah tebal asap yang
berlomba menggapai langit-langit. Atau bergurau mengomentari tingkah para pemula yang
tersipu malu melihat bolanya menyusur parit tepi lintasan. Namun, adakalanya kami
berbincang serius setelah tak lagi peduli pada kata-kata minus polesan. Atau saling
meledek tanpa sakit hati. Kecerdasan dan kejenakaannya membuatku nyaman.
"Pasti kamu punya pikiran jelek tentang aku," satu kali dia berkata
tiba-tiba.
"Kenapa? Karena orang yang kamu temani?" aku menebak.
Julia mengangguk, tak lepas menatapku dengan sorot mata kanak-kanak yang menuntut
jawaban paling jujur.
"Bukan jelek, hanya buram," elakku bergurau. Kuhirup rokok dalam-dalam lalu
mengepulkan asapnya ke atas membentuk lingkaran tebal berpilin.
"Kamu baik. Tak pernah hunjamkan pandang merendahkan," katanya lagi.
"Kenapa harus begitu? Pilihan dan kemauan tidaklah sama ukurannya bagi tiap
orang."
"Jika pilihan itu bukan dari kemauan orang itu sendiri tapi pilihan dan kemauan
orang lain?"
"Apa yang kamu harapkan? Belaskasihan? Jangankan airmata, darah pun tak ada
harganya. Kita sendiri yang tentukan siapa kita di dunia yang tidak adil ini dengan apa
pun yang kita miliki kini."
"Termasuk menjadi sepertiku?"
"Lihat, kamulah yang menilai rendah diri sendiri! Tahu apa aku tentang kenyataan
yang terjadi pada diri kamu sehingga berhak menilai pembenaran yang kamu ambil? Tidak
ada."
"Kalau kamu tahu ... ?" tanyanya menggantung.
"Jangan paksa aku jadi orang suci."
Julia terdiam sejenak. Asap rokok di jemarinya mendaki atmosfer pelan-pelan. Aku
sengaja menunggu.
Sambil mematikan rokok dia berkata, "Aku anak sulung dari tiga bersaudara,
perempuan semua, dari keluarga biasa. Kaya tidak, miskin tidak, terkenal pun tidak. Hanya
jambon krislam seperti banyak orang lain."
"Jambon krislam?" aku tak paham.
"Bapak Jawa, ibu Ambon. Ibu Kristen, bapak Islam," dia tertawa senang melihat
kerut keningku. Matanya ikut tertawa. Aku memencongkan mulut.
"Sore itu kami bertiga sedang pulang melalui jalan yang setiap hari kami lalui
ketika sekelompok lelaki menyergap dan menyeret kami ke dalam hutan. Kepalaku diselubungi
kain, tak bisa melihat apa yang terjadi pada kedua adikku. Hanya jeritan mereka yang
kudengar ditingkah suara pukulan, makian dan tawa lelaki, serta kain koyak. Kian keras
mereka menjerit, kian kerap pukulan kudengar, hingga akhirnya jeritan mereka melemah dan
lenyap. Aku tahu, yang mereka alami sama seperti yang kualami, dianiaya dan
diperkosa."
Telinga kupaksa menepis gaduh hantaman bola boling. Wajah eksotisnya bagai petang yang
sekonyong-konyong diringkus malam.
"Apa yang mereka incar dari seorang novis berkawan dua perempuan kecil berseragam
sekolah lanjutan pertama? Keluarga kami bukan tokoh masyarakat, bukan penggiat gereja atau
mesjid, bukan pula anggota laskar. Kenapa kami?"
Mulutku terkunci. Layar di benakku mengilaskan tragedi kelam yang melanda kepulauan
rempah-rempah bertahun silam.
"Sia-sia meronta. Bertubi pukulan ke badan dan kepala membuatku tak mampu bertahan
tetap sadar. Saat siuman, kutemukan diriku terkapar telanjang berkubang lumpur. Perih luka
dan memar melumpuhkan seluruh sendi. Kepala tak lagi berselubung. Langit di atas amat
gelap. Hutan begitu senyap. Kuseru nama kedua adikku sekuat tenaga, tapi hanya bisik
berludah darah yang terucap. Berulangkali kucoba, tiada bersahut. Aku melata sambil
meraba-raba hingga akhirnya menyentuh benda lunak hangat. Adik bungsuku. Kukenali dari
parut di lengan kirinya. Telanjang berlumur lumpur, leher mengangakan luka, kepala
terkulai nyaris terpisah dari tubuhnya. Gerimis di gelap malam jadi ganti tangis yang tak
sanggup kulakukan."
"Tidak usah diteruskan jika membuatmu tak nyaman," hiburku saat dia tersuruk
dalam diam. Halimun kelabu bergulung-gulung di telaga gelap tanpa airmata.
"Enggankah kamu jadi pendengar cerita tak indah?" todongnya.
"Haruskah bercerita kepadaku yang hanya seorang asing bagimu?" balasku.
"Kamu Aldo. Aku Julia," katanya sambil menganjurkan tangan kanannya. Kami
bersalaman seperti baru berkenalan. "Nah, sekarang kita bukan lagi orang asing satu
sama lain," sambungnya menirukan dialog dari film yang kulupa judulnya. Aku
menyeringai sepat.
Belum sempat dia lanjutkan kisahnya, kulihat Ronny melambai dari depan meja kasir.
Kukedipkan mata pada Julia memberi isyarat aku harus pulang. Dia mengangguk tanpa kecewa.
"Besok ada waktu?" tanyanya sebelum aku beranjak.
Biasanya tak ada kegiatanku hari Sabtu. "Kuhubungi besok," kataku sambil
mengeluarkan PDA hendak mencatat nomor ponselnya.
"Tidak usah. Aku akan ada di sini," elaknya halus.
Kuhampiri Ronny. Sepanjang jalan, aku hanya diam. Ronny pun tak berselera bicara.
Mungkin kesal karena kalah dalam permainan.
From: jdf83@...
Date: Wednesday, 30 July 2008 21:34
dear aldo,
sebentar lagi burung besi gemuk itu membawaku melintas laut dan benua ke tempat yang
belum pernah kubayangkan sekalipun dalam khayal, sebuah negeri yang tiruan saljunya dulu
kerap kulihat di dedaunan cemara natal. kata orang, di sana semua mimpi tak lagi mustahil.
sayangnya aku tak berani bermimpi, hanya bersedia diri mendada hari sekuat badan dan jiwa,
apa pun taruhannya.
banyak yang sudah dan akan kamu dengar dari ronny ataupun orang lain. tak akan
kusangkal meski bukan itu kesejatian yang erat meringkuk di pojok paling rahasia diriku.
kamu pun tak sepenuhnya tahu biarpun kamu satu-satunya orang yang kututuri perihalku. apa
pun kata mereka, janganlah turut menjadi hakimku, sebagaimana aku pun tak akan mengutuk
noktah hidupku sebagai dosa orang lain.
julia namaku. dari nama bulan pertama paruh kedua tahun. aku tak percaya takdir, tapi
pilihan dan kemauan. kuingin langkahku kini jadi pijakan pertama merengkuh kesempatan
kedua dari pilihan yang kutetapkan sendiri.
harapkan aku tak patah dan kalah. doakan aku jika kamu masih percaya doa.
penuh sayang,
julia
Malam mendaki remaja.
* * *
Langit Sabtu berundung awan. Julia menawan seluruh petang dan setengah malamku lewat
kisahnya.
Dia peluki jasad adik bungsunya dalam hujan, tak henti membisikkan namanya sepanjang
malam hingga fajar menyeruak dari balik pepohonan sagu. Beberapa orang kampung yang lewat
lantas menolongnya. Adik keduanya tidak pernah ditemukan.
Saat pulang, cuma arang membara dan puing berasap yang dia dapatkan. Genap sudah
kemusnahan seketika. Tak sesuatu dan seorang pun tersisa sebagai alasan tetap tinggal.
Hampa hari menuntun galaunya ke pelabuhan. Ingin dia luruhkan segalanya ke buih ombak yang
menyerpih diiris lunas kapal yang membawanya ke Surabaya.
Namun, malam pekat berhujan di hutan sagu bersikeras memburu lewat ingatan maupun
mimpi-mimpi yang senantiasa memaksanya terjaga bersimbah peluh. Tidur jadi sangat
menakutkan. Dia larikan dirinya mengejar malam tanpa kegelapan. Profesi pramuria karaoke
menyeretnya ke keping waktu padat rahasia. Cengkeraman pelik kemilau semu malam
mendesaknya ke sisi paling muram seorang perempuan.
"Setelah semua direnggut paksa, masih haruskah kenajisan diludahkan pada perempuan
yang memakai tubuhnya, satu-satunya milik yang tersisa, untuk bertahan? Seks tak lagi
berurusan dengan kesakralan maupun rajut terhalus perasaan manusia, melainkan transaksi
menunda lapar. Dan, bagiku, sebagai senjata perlawanan. Mereka memujanya, aku menistanya.
Kucibir mereka yang terkapar kalah di hadapan seks yang mereka kejar," tutur Julia
tanpa nada berapi-api.
Jeda sejenak sebelum dia menyambung, "Tapi, adalah munafik jika kukatakan tak
pernah sekali pun menikmatinya. Seperti orang lain, aku pun punya birahi. Dan tak bisa
kubunuh angan untuk merasainya sepenuh-jiwa sepenuh-tubuh bersama lelaki yang sanggup
berdamai dengan keberadaanku."
"Seperti film Pretty Woman?" cetusku mencoba mengikis getir.
"Begitulah," timpalnya ringan. "Nyaris aku terbebas dari jerat
kemenduaan itu saat kujumpa Ronny."
Serta-merta tenggorokanku tercekat. Alis mata kananku terangkat. Ronny? Anggukan Julia
menjadi konfirmasi.
"Tapi aku tidak terlalu bodoh untuk memahami siapa diriku dan siapa Ronny. Pretty
Woman adalah senandung orang yang mampu bersegera selaraskan diri seturut perkembangan
keberadaan orang lain. Sedangkan kita masih selalu memperhitungkan masa lalu sebagai
ukuran martabat."
"Tapi, Ronny ..."
"Setidaknya, dia menyadarkanku bahwa kubangan pun ada tingkatannya," potong
Julia tertawa, "yang tidak mustahil ditembus di Jakarta ini."
Lidahku kelu. Meski kutahu Ronny jauh dari alim, tak pernah kuharap menyua sosok
fragmen masa lalunya.
"Tak usah dipusingkan. Aku saja tidak kenapa-napa, malah kamu yang loyo seperti
baru dilabrak debt collector," gurau Julia membuyarkan kecamuk pikiranku.
"Aku jadi curiga kamu mendekatiku karena Ronny," gumamku murung.
Julia menampar pelan pipiku sambil mencibir. Bukan marah, sebab kulihat senyum menari
di matanya.
"Paranoid! Kamu kira aku anak kencur yang ingin pacarnya cemburu?"
"Lalu kenapa?"
"Sebab aku suka kamu," bisiknya tanpa menundukkan pandang.
Gubraaaak! Mungkin itulah seruan remaja jaman sekarang yang jitu memerikan
perasaanku. Melongo adalah satu-satunya ekspresi yang bisa kutampilkan.
"Jangan pasang tampang bloon gitu, ah!" tegur Julia sambil
menggoyang-goyangkan daguku.
Aku masih belum bisa bereaksi.
"Terlarangkah bagiku untuk menyukaimu? Terlalu tinggikah kamu untuk kusukai?"
desaknya membelalak. Senyum masih menari di matanya.
Julia, aku hanyalah seorang lelaki periferal. Pengakuan seperti itu bukanlah hal biasa
buatku.
"Jika demikian, kenapa aku repot-repot ke sini?" gerutuku melepaskan diri
dari debar.
"Entah. Mungkin mengharap seks ...," sahutnya acuh tak acuh.
"Dasar otak kotor, mulut juga kotor!" geramku sambil menuding mulutnya.
"Memangnya tidak pernah terpikir? Ayo, ngaku!" ganti dia menuding pelipisku.
Telanjur masuk gelanggang, sekalian sajalah bertarung. "Sangkamu aku lelaki buta
tuna imajinasi?"
Julia menatap mataku seakan hendak menerobos ke dalam. Dengan lembut diraihnya kepalaku
mendekat ke arahnya. Di luar, gerimis turun malu-malu dalam lagu.
From: jdf83@...
Date: Friday, 1 August 2008 07:47
dear aldo,
aku baru tiba di negeri yang bekunya masih belum bisa kuakrabi. kutulis email ini di
café sambil menunggu kereta. secangkir cappuccino hangat dan zippo tuamu mengawaniku.
tapi aku masih sanggup bertahan tidak menyalakan rokok.
sabtu sore itu, nyaris tak luput kutatapi pintu, berharap kamu segera tiba walau kamu
tak pernah janji. senyum pasti menari di mataku (begitu istilahmu) saat hadirmu memupus 5
jam penantian paling meresahkan.
itulah kali terakhir pertemuan kita. kamu terkejut saat kukatakan bahwa kamu
satu-satunya orang yang kupamiti. memang tak ada siapa-siapa yang bukan orang asing
bagiku. tidak pak ishak, tidak ronny, atau siapa pun yang bahkan pernah berbagi selimut
denganku. hanya kamu, yang sebatas berbagi rokok, waktu, dan kata. toh tak semua
percintaan bermeterai persebadanan, katamu.
diniary namaku. dari "dini hari". aku percaya janji mentari yang akan selalu
berjuang datang saat subuh menjelang. kuingin hari tersulit yang kusongsong kini jadi
fajar pemupus pekat meski harus merangkak lambat.
dear aldo, keretaku sudah tiba. belum sepadan terimakasihku atas semua perjumpaan kita
yang membuatku tak putus berharap ada pagi di ujung lorong dan semua akan baik-baik saja.
dengan cinta,
diniary
Malam kian meranum dewasa.
* * *
Aku tidak mengawani Ronny ke tempat boling. Batuk dan pilek menyerangku membabi-buta.
Bunyi komputer tanda datangnya email memaksaku turun dari ranjang.
From: jdf83@...
Date: Saturday, 2 August 2008 04:23
dear aldo,
fajar baru saja bangkit menciumi embun di balik kaca jendela. satu malam berlalu lagi,
satu perjalanan pun usai sudah. namun, untaian tualang sejati temukan tempat dan makna,
baru saja bermula, di hamparan lenan putih yang menantiku melangkah.
aku percaya segala sesuatu mengalir. kini aku pun akan mengalir. ke atas, melampaui
lapis teratas kubangan. kuharap kota kecil yang namanya mungkin belum pernah kamu dengar
ini tak menuntut daya lompat sedahsyat jakarta :-) setidaknya, tak ada yang mengukuriku
lewat teropong masa lalu.
fitria namaku. dari "fitri". kuingin lahir kembali seperti bayi yang tak
berbeban dosa kala menyapa dunia dengan ketelanjangan dan tangisan.
ya, aku telanjang saat ini, aldo. kumau memasuki dan dirasuki sejarah baru dengan
kepolosan paling hakiki. kuingin menyapamu seutuh diri tanpa selubung, hanya berbatas
udara yang dulu kerap kita gambari dengan asap.
aku juga menangis, aldo. bukan bersebabkan ketelanjangan-luka-memar berlumur lumpur di
hutan sagu ataupun ranjang masai berkeringat, melainkan dari rasa paling purba yang telah
kulabuhkan kekal di satu sabtu, menyimpul tuntas geligi masa lalu yang dengannya aku telah
berdamai.
dear aldo, dentang lonceng doa pagi memanggil. aku harus bergegas. maklum, aku belum
cukup mahir memasang tudung kepala :-)
dalam kasih,
fitria
ps. alamat ini akan kututup setelah email ini terkirim. tak usah kita rindukan masa
datang. biarlah semua mengalir.
Ada yang diam-diam menyelinap lolos dari pusat diriku. Rasa kehilangan yang teramat
sangat. Seorang perempuan bukan rumahan dan bukan sekolahan. Bukan kriteria idamanku.
Namun satu-satunya yang pernah menghelaku dari sisi periferal menjadi orang pertama bahkan
satu-satunya.
Adieu, Julia Diniary Fitria. Panta rhei.
Malam kian menyuruk renta. Hari esok mematri janji kisah berbeda.
— PinAng: Minggu, 3 Agustus 2008 04:01
[*] panta rhei (Gerika) = segala sesuatu ada dan berubah dalam aliran.
untuk seseorang yang namanya jadi ilham meski bukan tokoh nyata kisah di
atas